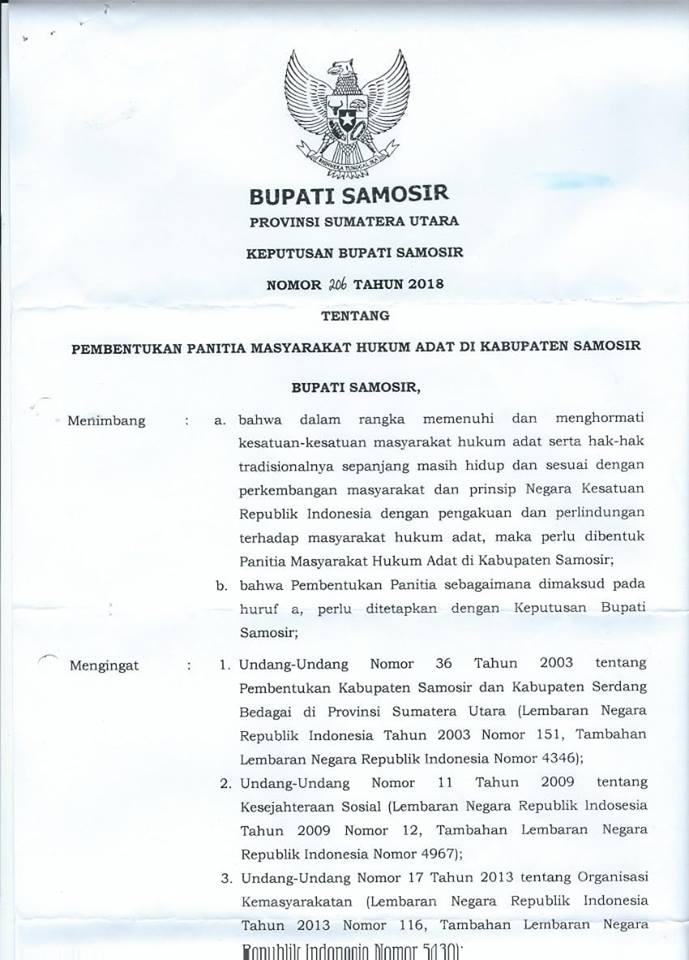Sejumlah alasan mengapa PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak relevan di Tano Batak karena mengakibatkan krisis sosial-ekologis dan alternatif solusinya
Oleh: Hardo Manik
Krisis sosio-ekologis sedang mendera dunia yang kita huni. Organisasi Meteorologi Dunia memperkirakan bahwa suhu global akan melewati ambang batas kritis 1,5°C dalam lima tahun ke depan dan 2,7°C pada akhir abad ini (World Metereological Organization, 2023). Akibatnya, setidaknya dua miliar orang akan tinggal di zona yang terlalu panas, yang membahayakan kesehatan, produktivitas kerja, keamanan air, dan kualitas udara (Lenton et al., 2023). Terkait masalah hilangnya keanekaragaman hayati, The Living Planet Report 2022 mengungkapkan adanya penurunan populasi mamalia, burung, ikan, reptil, dan amfibi sebesar 68% sejak tahun 1970 (WWF, 2022). Tingginya laju deforestasi memperparah kerusakan ekosistem alam di mana sekitar sepuluh juta hektar hutan digunduli setiap tahunnya untuk perkebunan monokultur seperti eukaliptus dan sawit (FAO, 2020). Hilangnya keanekaragaman hayati pada akhirnya akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan mengancam kesejahteraan manusia dan makhluk hidup non-manusia (Isbell et al., 2023).

Berbagai Komunitas Masyarakat Adat di dunia sebetulnya terbukti memainkan peran krusial sejak zaman dulu dalam menjaga hutan dan laut tetap lestari (Abas et al., 2022; Scheidel et al., 2023). Namun, mereka sedang menghadapi konflik akibat pemerintah dan perusahaan-perusahaan ekstraktif mengambil wilayah adat tanpa persetujuan mereka untuk kepentingan bisnis kapitalistik atas nama investasi dan pembukaan lapangan kerja. Analisis 3081 konflik lingkungan di dunia yang dilakukan oleh Scheidel et al. (2023) menemukan bahwa setidaknya 34% kasus tersebut melibatkan Masyarakat Adat yang mayoritas berhadapan dengan perusahaan tambang, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Studi tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa Masyarakat Adat secara global telah menderita kehilangan sumber penghidupan, kehancuran budaya, dan kehilangan tanah. Tidak terkecuali di Indonesia, laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga mengungkap kasus-kasus serupa yang hampir merata terjadi di berbagai daerah (Savitri et al., 2019).
Tulisan ini secara khusus fokus mengangkat contoh kasus konflik antara Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menguraikan sejumlah alasan mengapa TPL perlu ditutup dari perspektif studi manajemen kritis. Saya juga sangat mendukung inisiatif AMAN mengembangkan Koperasi Produksi sebagai alternatif solusi demi kemandirian ekonomi Masyarakat Adat di Tano Batak berbasis keberagaman potensi lokal.
Toba Pulp Lestari (TPL) adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual bubur kertas (pulp) dari bahan baku eukaliptus. Sebelum berganti nama, PT. TPL bernama PT Inti Indorayon Utama yang memproduksi rayon (bahan penting untuk tekstil). Perusahaan ini didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto dan memperoleh izin pemerintah pada akhir tahun 1983. Menurut data Forbes 2023, Sukanto Tanoto menempati urutan ke-20 orang terkaya dengan total kekayaan US$ 3,15 Miliar atau sekitar Rp 48 triliun. Dirangkum dari berbagai sumber (Laporan Tempo, Beritasatu), taipan satu ini menguasai lahan yang sangat luas di Indonesia di bawah induk korporasi Royal Golden Eagle (RGE), misalnya 48 ribu hektar lahan di daerah ibu kota baru yang merupakan konsesi PT ITCI Hutan Manunggal (IHM) Kalimantan Timur dan sekitar 980.000 hektare konsesi hutan kayu perusahaan pulp dan kertas Asia Pasific Resources International Limited (APRIL). TPL sendiri, menurut izin konsesi terbaru tahun 2020, memiliki konsesi lebih dari 167.912 hektare. TPL telah berkonflik dengan berbagai Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak lebih dari 30 tahun akibat perampasan wilayah adat demi ekspansi bisnisnya (lihat website Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat, AMAN, atau Bakumsu untuk rincian lengkap sejarah konfliknya). Sebelum lebih jauh berargumentasi, saya perlu terlebih dahulu memperkenalkan diri dan pijakan nilai-nilai saya sebagai seorang akademisi manajemen.

Posisionalitas saya sebagai akademisi
Literatur-literatur metodologi penelitian, terutama yang berparadigma kritis, mengajarkan saya untuk mengungkapkan posisi nilai-nilai saya dan sejauh mana itu membentuk cara saya dalam memproduksi pengetahuan dan mengambil sikap keberpihakan. Bagi saya, tidak ada ilmu pengetahuan yang netral. Semua dibentuk oleh posisi politik dan kepentingan produksi pengetahuan.
Saya adalah dosen di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta dan mahasiswa doktoral di Sekolah Bisnis, University of Queensland, Australia. Dengan izin, dukungan, dan masukan kritis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saya sedang melakukan penelitian Kearifan Adat dalam konteks konflik kepentingan bisnis dan ekologi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk Tano Batak. Alih-alih mengikuti mazhab arus utama manajemen yang mengagung-agungkan perusahaan dan bisnis seolah tanpa cela dan dosa, sebagai akademisi manajemen, saya memilih untuk menghayati pendekatan Studi Manajemen Kritis dan Dekolonisasi Bisnis. Studi Manajemen Kritis mengkritisi pendidikan bisnis arus utama yang menganggap bisnis bebas nilai dan tidak masalah untuk mengeksploitasi buruh dan alam demi memperoleh laba yang besar (Adler et al., 2007). Studi yang berkembang pesat di Inggris dari gerakan Partai Buruh ini fokus membongkar penindasan dan eksploitasi di perusahaan dan sering mengambil inspirasi dari tradisi Marxis dan teori-teori postmodernisme dan poststrukturalisme (Adler et al., 2007; King & Learmonth, 2015).
Sementara itu, Dekolonisasi Manajemen dan Bisnis mengembangkan lensa kritis untuk menginterogasi berbagai hierarki-hierarki dan penindasan-penindasan yang dihasilkan oleh kolonialisme—seperti perbudakan modern buruh dan pelestarian hierarki bahasa, epistemik, spiritual, ekologis, gender, dan rasial antara pengetahuan Barat/Eropasentris dengan pengetahuan Adat —dalam studi manajemen dan bisnis (Banerjee, 2022b). Sederhananya, mendekolonisasi teori dan praktik manajemen dan bisnis berarti mengakui adanya penjajahan pengetahuan dimana hanya sistem pengetahuan Barat yang dianggap beradab dan berhak meneliti dan mendikte sejarah dan pengetahuan kita sendiri. Contohnya, para peneliti Belanda mempelajari potensi kekayaan alam, ekonomi, dan budaya Indonesia, termasuk Tano Batak, dengan tujuan untuk menjajah. Mereka kemudian mengkampanyekan bahwa pengetahuan-pengetahuan Adat di Indonesia primitif dan tidak beradab agar leluhur kita kehilangan kepercayaan diri terhadap pengetahuan dan kearifannya sendiri. Sementara itu, mereka merampas artefak-artefak dan berbagai arsip-arsip kuno agar kita kesulitan mempelajari sejarah kita sendiri dan kehilangan identitas dan kebanggaan pada mahakarya dan kearifan para leluhur kita. Di titik inilah gentingnya mendekolonisasi pengetahuan warisan penjajah di sistem pengetahuan kita.
Saya juga adalah orang Batak, bermarga Manik. Memiliki marga berarti saya memiliki tanggungjawab untuk menjaga tanah Adat yang diwariskan leluhur dan melestarikan kebudayaan bangsa Batak. Saya juga masih terus mempelajari sejarah penjajahan Belanda atas Tano Batak dan sejauh mana ini membuat bangsa Batak, termasuk saya, memiliki mental hatoban (mental budak), tidak berpikir mandiri, dan krisis identitas sebagai orang Batak. Saya juga sedang terus belajar dan menghayati pengetahuan dan kearifan adat Batak sampai hari ini. Tujuannya adalah untuk mendekolonisasi pikiran saya dari pengetahuan-pengetahuan Barat yang dianggap lebih unggul yang banyak mempengaruhi cara berpikir saya ketika dididik di sekolah-sekolah formal.
Sejumlah alasan mengapa TPL perlu ditutup
Dengan rangkaian panjang konflik agraria antara TPL dan Masyarakat Adat di Tano Batak yang akar masalahnya adalah klaim sepihak negara atas wilayah adat dan ekspansi kapitalistik TPL dengan tujuan semakin memperkaya konglomerat Sukanto Tanoto, saya mengusulkan izin konsesi TPL dicabut dengan beberapa alasan.
Pertama, TPL beroperasi dengan sistem pengetahuan bisnis yang antroposen dan kapitalosen. Sistem pengetahuan bisnis yang antroposen artinya alam hanya dianggap berguna sejauh memberikan manfaat untuk kepentingan manusia. Tetapi apakah semua manusia? Tidak. Oleh karena itu, istilah baru muncul: kapitalosen. Artinya adalah alam hanya dianggap berguna sejauh memberikan manfaat untuk memperkaya segelintir kapitalis atau oligarki (Moore, 2017, 2018), dalam hal ini, Sukanto Tanoto. Dua cara pandang ini berakar pada filosofi positivisme Barat bahwa kepentingan egois manusia adalah di atas segala-galanya walaupun harus memperkosa hak asasi manusia dan hak asasi alam. Filosofi ini juga menganggap bahwa segala kerusakan alam, spiritual, adat istiadat atau budaya tidak relevan dalam hitung-hitungan ekonomi. Lawan dari pandangan ini adalah ekosentrisme, bahwa alam itu hidup dan memiliki hak asasi terlepas dari kepentingan manusia.

Bagi TPL, segala hal di alam yang berwujud dapat dieksploitasi untuk kepentingan bisnisnya. TPL tidak peduli dengan berbagai Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak kehilangan relasi spiritual dengan hutan haminjon (kemenyan) akibat penebangan hutan alam. Berdasarkan beberapa video dan publikasi media, ketika TPL ditanya terkait dengan tuduhaan telah merusak wilayah adat, responnya normatif legal formal bahwa mereka telah memperoleh izin dari negara dan tidak merespon substansi terkait respon perusakan ritual-ritual adat dan hutan adat. Pengetahuan bisnis semacam ini merupakan warisan pengetahuan penjajah Barat yang dipaksakan ke Indonesia, termasuk Tano Batak. Bagi penjajah, pengetahuan yang modern dan ‘beradab’ hanyalah pengetahuan dan filosofi yang dikembangkan Eropa, terutama pengetahuan ekspansi bisnis kapitalistik, sementara pengetahuan dan kearifan adat di berbagai negara jajahan, termasuk Indonesia, dianggap primitif. Sampai hari ini, pengetahuan bisnis semacam ini masih lestari dipelajari di fakultas-fakultas bisnis di Indonesia sehingga penjajahan epistemik masih berlangsung. Beberapa peneliti studi manajemen kritis dan dekolonisasi bisnis (Banerjee & Arjaliès, 2021; Banerjee & Berrier-Lucas, 2022; Parker, 2018) bahkan sampai menyerukan agar fakultas-fakultas bisnis direvolusi atau bahkan ditutup karena bertanggungjawab atas ketimpangan dan kerusakan alam akibat mengajarkan keberpihakan terhadap para oligarki.
Kedua, konsesi penguasaan oleh TPL mencerminkan ketimpangan penguasaan tanah dan mandegnya reforma agraria di Indonesia. Menurut data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2021, 68 persen tanah di daratan Indonesia adalah milik satu persen kelompok konglomerat dan korporasi besar. Rakyat 99% memperebutkan sisanya. Secara khusus, TPL menguasai konsesi lebih dari 167.000 hektar lahan. Sementara itu, menurut data Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, tuntutan wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan adalah sekitar 20.754 hektar dan mayoritas belum diakui sampai hari ini. Ini sangat timpang dan tidak adil.
Selain itu, TPL juga merusak keanekaragaman hayati dengan ekspansi tanaman monokultur eukaliptus di lahan seluas itu. Perkebunan monokultur berbahaya untuk keberlanjutan alam karena menebangi hutan alam yang akibatnya menghancurkan ekosistem keanekaragaman hayati (Shiva, 2020). Bagi saya, laporan keberlanjutan perusahaan tahunan hanyalah omong kosong dan pencitraan jika yang dikembangkan adalah perkebunan monokultur. Logika keberlanjutan alam sejati berdiri di atas dasar keanekaragaman hayati, bukan penyeragaman atas nama kepentingan produksi korporasi yang memperkaya segelintir kapitalis (Shiva, 2015, 2020).
Warisan struktur ekonomi yang timpang tersebut merupakan warisan penjajah yang Indonesia tidak pernah serius untuk memperbaikinya dengan agenda reforma agraria sesuai amanat UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Perilaku penjajah belum sirna di Indonesia: selalu menganggap tanah dan hutan sebagai terra nulius atau tanah kosong sehingga negara atau perusahaan merasa berhak untuk mendudukinya demi kepentingan akumulasi kapital. Akibat pendudukan itu, TPL mengkriminalisasi para pejuang Masyarakat Adat yang berjuang mempertahankan tanahnya sama seperti dulu para pejuang kemerdekaan Indonesia dikriminalisasi oleh penjajah karena mempertahankan tanah tumpah darah. Ada relasi kuasa yang timpang antara TPL dan Masyarakat Adat. TPL dengan segala kuasa kapital dan jejaring politiknya memiliki kuasa yang yang lebih besar dibanding Masyarakat Adat sehingga semena-mena melaporkan ke aparat. Pemerintah sebetulnya perlu berpihak pada rakyat kebanyakan dengan mematuhi agenda reforma agraria dan melindungi Masyarakat Adat dengan mematuhi UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan mensahkan RUU Masyarakat Adat.
Ketiga, TPL merusak sistem budaya Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat (KMA) di Tano Batak. Budaya adalah hasil interaksi manusia dengan Tuhan, leluhur, dan alam. KMA-KMA di Tano Batak, misalnya KMA Sihaporas (Kabupaten Simalungun), KMA Dolok Parmonangan (Kabupaten Simalungun), dan KMA Tornauli (Kabupaten Tapanuli Utara) melaksanakan ritual-ritual adat sebagai ekspresi relasi hormat mereka dengan Mulajadi Nabolon (Tuhan), leluhur, dan alam (Manalu et al., 2021). Bahan-bahan ritual adat diambil langsung dari hutan adat (Manalu et al., 2021). Selain tanaman-tanaman dari hutan adat, air dari mata air jernih juga termasuk menjadi bahan ritual. Eukaliptus yang ditanami TPL tentu saja bukanlah bahan untuk ritual adat. Mata air tercemar akibat penggunaan insektisida, fungisida, dan herbisida untuk penanaman dan pemeliharaan eukaliptus yang sangat masif juga tidak dapat digunakan untuk ritual. Menurut UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, adat istiadat dan ritus adalah bagian Objek Pemajuan Kebudayaan yang harus dilindungi. Pemerintah harus tegas menuntut TPL telah merusak Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut.
Keempat, negara dan TPL tidak mengimplementasikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sedari awal sebelum menduduki wilayah adat di Tano Batak sejak perusahaan ini didirikan tahun 1983. FPIC adalah mekanisme etika bisnis yang mengakui hak Masyarakat Adat untuk mengatakan “ya dan bagaimana” maupun “tidak” setelah suatu perusahaan menjelaskan secara transparan apa tujuan menggunakan tanah, bisnis apa yang akan dibuka, apa dampak sosial-budaya-lingkungannya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh Masyarakat Adat. Musyawarah Adat adalah mekanisme Komunitas Masyarakat Adat untuk mengambil keputusan menerima atau menolak tanpa diintervensi atau diinteli aparat. Perjalanan saya mewawancarai para beberapa ketua Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak mengonfirmasi tidak adanya proses FPIC tersebut. Polanya mirip dengan sejarah ekspansi agraria di Tano Batak dimana pemerintah kolonial memberikan izin penggunaan tanah ulayat ke para pemilik perkebunan besar dengan tanpa izin dan sepengetahuan Masyarakat Adat (Azhari & Sinaga, 2022).
FPIC itu mutlak dilakukan karena para leluhur setiap Komunitas Masyarakat Adat sudah terlebih dahulu menempati wilayah adat jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan dan TPL berdiri. Oleh karena itu, Masyarakat Adat bukan pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan yang kepentingan penghidupannya dapat dinegosiasikan, tetapi pemegang hak (rightsholder) yang hak-haknya harus diakui dan dilindungi. Mereka punya kedaulatan untuk menolak jika merasa masuknya bisnis akan membahayakan ruang hidup mereka. Namun, literatur mengungkap perusahaan juga seringkali mengkondisikan persetujuan (manufacturing consent) Masyarakat Adat dengan ‘menyuap’ dan memecah belah Masyarakat Adat menggunakan dana sosial perusahaan atau permainan aparat atau birokrat negara (Choudhury & Aga, 2020). Ini juga sekalian menjadi kritik terhadap teori pemangku kepentingan yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis (Freeman et al., 2020; Parmar et al., 2010). Teori pemangku kepentingan didasarkan pada asumsi bahwa pihak yang memiliki kuasa dan kepentingan paling kuat akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan pihak yang kuasa dan kepentingannya lemah (Banerjee, 2000, 2003). Teori ini tidak memiliki dimensi keadilan sosial.

Kelima, model bisnis TPL tidak demokratis karena hanya memperkaya konglomerat Tanoto dan direksinya serta eksploitatif terhadap buruh. Saham adalah cerminan kepemilikan perusahaan dan kuasa. Mayoritas laba TPL tentu saja masuk ke kantong Sukanto Tanoto sebagai pemilik saham mayoritas. Ibarat kue bolu loyang, sekitar ¾ bagiannya adalah milik Sukanto Tanoto, sementara sisanya dibagi-bagi pada buruh sebagai gaji. Buruh juga tidak memiliki saham pada perusahaan sehingga tidak berhak memilih direksi dan bersama-sama merumuskan kebijakan strategis perusahaan. Dengan kata lain, hanya segelintir elit yang mengambil keputusan bisnis TPL. Bahkan, Masyarakat Adat sendiri pun tidak diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya terkait kebijakan bisnis TPL dalam Rapat Umum Pemegang Saham akibat tidak memiliki saham di perusahaan ini yang harusnya menjadi hak mereka atas penggunaan wilayah adat.
Klaim pembukaan lapangan kerja juga hanya mitos. Menurut Laporan Keberlanjutan TPL tahun 2022, perusahaan ini memiliki karyawan tetap hanya 1.169 orang, karyawan sementara 69 orang, dan 6.072 orang karyawan tidak langsung/kontraktor. Jika klaimnya adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, jumlah ini sangat sedikit berbanding penguasaan lahan lebih dari 167.000 hektar. Atas nama efisiensi, TPL melakukan strategi penjajahan: upah murah, jumlah buruh sedikit, dan beban kerja berlebih. Studi gabungan oleh DPD GSBI Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), AMAN Tano Batak, Bakumsu, Walhi Sumut, Serikat Tani Tobasa dan Aliansi Gerak Tutup TPL pada tahun 2021 mengungkap ironi bahwa buruh TPL rata-rata menerima upah Rp 1,87 juta bahkan banyak di bawah Rp. 1 juta. Studi yang sama juga menemukan peniadaan lembur, tempat tinggal yang layak, hak cuti, dan hak istirahat kerja pada buruh TPL. Saya tidak menemukan data berapa gaji direksi TPL per bulan tetapi dugaan saya pasti sangat besar sehingga rasio ketimpangan pendapatan antara direksi dengan buruh kemungkinan sangat tinggi.
Keenam, klaim penyaluran dana sosial perusahaan TPL terhadap masyarakat tidak akan dapat mengembalikan hutan dan budaya yang telah rusak. Kita butuh beratus tahun untuk mengembalikan hutan alam yang rusak agar ekosistemnya lestari kembali lagi. Tidak mudah juga mengembalikan budaya dan relasi sosial yang rusak. Semua itu terlalu sulit diukur dengan uang. Berdasarkan lensa studi manajemen kritis, pemberian dana semacam itu juga tidak lepas dari kepentingan politik. Perusahaan seringkali menggunakan dana tersebut mengadu domba sesama rakyat, membungkam suara-suara kritis, dan sebagai ‘bom asap’ untuk menutupi dosa-dosa lingkungannya (Banerjee, 2008, 2022a). Mari kita cek misalnya kampus-kampus yang menerima dana sosial TPL untuk pembangunan gedung atau keperluan kampus lainnya maupun mahasiswa-mahasiswa yang menerima Beasiswa Tanoto Foundation. Apakah mereka berani kritis terhadap TPL atas kerusakan-kerusakan sosio-ekologis yang terjadi di Tano Batak?
Ketujuh, TPL diduga melakukan pengalihan keuntungan yang menyebabkan kebocoran pajak di Indonesia. Laporan oleh Koalisi Forum Pajak Berkeadilan tahun 2020 mengungkap bahwa kerugian potensi pajak yang diderita pemerintah mencapai Rp 1,07 triliun tetapi TPL hanya membayar pajak US$ 15 juta. Menurut Majalah Tempo edisi 6 Februari 2021, TPL diduga memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke China untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri. Sementara itu, menurut majalah yang sama, Tanoto membeli gedung Ludwigstrasse 21 di Muenchen, Jerman, seharga Rp 6 triliun tetapi tidak tercatat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sehingga diduga menggunakan perusahaan cangkang untuk menghindari otoritas pajak di Jerman dan Indonesia. Masih menurut Majalah Tempo edisi yang sama, perusahaan Tanoto yang lain, Asian Agri Group juga pernah mengalami megaskandal rekayasa faktur pajak dan harus membayar denda Rp 2,5 triliun ke kas negara. Betapa merusaknya perusahaan ini! Herannya, pemerintah masih enggan mencabut izinnya.
Ringkasnya, pemerintah harus mengembalikan dan mengakui wilayah adat karena itu memang hak mereka. RUU Masyarakat Adat harus disahkan karena itu amanat konstitusi. Masyarakat Adat berkontribusi besar berjuang memerdekakan Republik ini. Bahkan Pancasila sendiripun merupakan titik temu nilai-nilai luhur Masyarakat Adat sebagaimana diakui oleh Sukarno sebagai salah satu penggalinya. Tetapi, lebih jauh, ideologi bisnis TPL sendiri harus dibongkar dan digugat. Tidak akan ada perdamaian antara bisnis dengan hak asasi manusia dan hak asasi alam jika ideologi bisnisnya kapitalistik. Sistem ekonomi yang mengakumulasi kekayaan di tangan segelintir orang tidak akan berhenti mengajarkan perusahaan untuk terus ekspansi bisnis dan merampas tanah rakyat demi memuaskan keserakahannya. Buruh dan Masyarakat Adat semakin tertindas. Apakah ada ideologi atau model bisnis alternatif yang manusiawi dan menghormati alam? Kita akan bahas di bagian berikutnya.
Perlawanan terhadap TPL dengan Strategi Pendidikan, Kebudayaan, dan Ekonomi
Sejauh literatur yang saya baca, hasil wawancara serta observasi langsung di lapangan, AMAN Tano Batak bersama jejaring mereka mereka konsisten bertahun-tahun membela hak-hak Masyarakat Adat di Tano Batak, terutama dari sisi advokasi hukum dan politik. Ini merupakan semangat Berdaulat Secara Politik dari AMAN. Perjuangan untuk mensahkan RUU Masyarakat Adat yang mandeg sampai sekarang harus terus didukung untuk memastikan wilayah adat diakui dan dilindungi di Indonesia. Kampus-kampus juga perlu bersuara dan berpihak pada perjuangan mereka demi kemanusiaan dan kelestarian alam.
Strategi berikutnya adalah pendidikan dan kebudayaan dengan bekerjasama erat bersama akademisi-akademisi yang memiliki keberpihakan yang sama. AMAN Tano Batak sudah menginisiasi pendidikan adat dan mengembangkan Sekolah-Sekolah Adat seperti Sekolah Adat Sihaporas dan Sekolah Adat Huta Lontung. Saya menyaksikan Sekolah Adat Sihaporas, misalnya, sudah berjalan untuk memastikan pengetahuan dan kearifan Batak diwariskan oleh para tetua komunitas sekaligus mengobarkan semangat perjuangan pada generasi muda melawan TPL. Memfasilitasi pendirian Sekolah Adat secara masif di Komunitas-Komunitas lainnya di Tano Batak akan semakin menguatkan perjuangan.

Lebih lanjut, AMAN Tano Batak bersama kampus-kampus yang relevan dapat bekerjasama meneliti dan mengembangkan sistem pengetahuan ekonomi dan bisnis berbasis kearifan adat Batak. Dalam hal ini, Masyarakat Adat Māori di Selandia Baru adalah salah satu contoh panutan. Akademisi-akademisi asli Māori yang bekerja di sejumlah kampus di Selandia Baru telah meneliti, menuliskan, dan mempraktikkan metodologi penelitian ala Māori dan sistem pengetahuan manajemen dan bisnis berbasis filosofi kearifan adat Māori. Sebut saja beberapa nama seperti Linda Tuhiwai Smith (penulis buku Dekolonisasi Metodologi) (Smith, 2021), Chellie Spiller, Amber Nicholson, Ella Henry, dan Edwina Pio (penulis Kearifan Organisasional, Manajemen, Inovasi, dan Kepemimpinan berbasis Filosofi Māori) (Henry et al., 2018; Nicholson et al., 2019; Spiller et al., 2011), dan masih banyak lagi. Saya pribadi siap terlibat bersama AMAN Tano Batak melakukan hal yang sama untuk meneliti sistem pengetahuan ekonomi dan bisnis berbasis kearifan Batak dan mengajarkannya di kampus untuk mendekolonisasi pengetahuan bisnis ala penjajah. Secara khusus, AMAN juga dapat mengembangkan protokol etika penelitian agar penelitian bersama Masyarakat Adat tidak berjalan ekstraktif demi semata-mata kepentingan si peneliti saja. Perlindungan kedaulatan data Masyarakat Adat juga perlu menjadi perhatian khusus.
Strategi berikutnya yang dapat dicoba adalah strategi perlawanan ekonomi. Alternatif pertama, menyuarakan pada pemerintah agar saham dan pengambilan keputusan strategis bisnis di TPL didemokratisasi. Pemerintah dapat memaksa TPL menerapkan kebijakan ESOP (Employee Share Ownership Plan). Kebijakan ini adalah membagi saham bagi pekerja dan Komunitas Masyarakat Adat secara berimbang agar mereka dapat memiliki hak suara penentuan kebijakan strategis perusahaan dan dapat memilih direksi perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham merupakan representasi kuasa kapital. Demokratisasi saham berarti demokratisasi kuasa. Dengan demikian, kuasa dan pengambilan keputusan bisnis tidak lagi terpusat di tangan Sukanto Tanoto seorang atau para elit direksi. Namun, mengharapkan pemerintah memaksa Sukanto Tanoto membagikan saham pada karyawan dan Masyarakat Adat sepertinya adalah ketidakmungkinan mengingat posisi tawar pemerintah terhadap oligarki dewasa ini semakin melemah karena kebutuhan dana politik yang sangat besar (Warburton, 2024).
Alternatif kedua dan juga yang sudah dari dulu disuarakan oleh Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat adalah tutup TPL! Sebagai ganti atau tandingan TPL, AMAN Tano Batak dapat mengorganisir Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak bersatu untuk mengembangkan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) Wilayah Tano Batak yang mengelola dan mengonsolidasikan produk-produk unggulan berbasis potensi lokal di setiap Komunitas Masyarakat Adat. Saya melihat panduan pendiriannya sudah disediakan oleh Pengurus Besar AMAN dan mencontohkan beberapa unit usaha yang berjalan sekarang seperti Gerai Nusantara di Bogor yang menjual kopi dan tenun.
Saya secara pribadi sangat mendukung pengembangan KPAM ini di Tano Batak karena sepakat dengan Suroto (2023) yang mengusulkan filosofi kooperativisme sebagai ideologi alternatif yang dapat menjadi lawan tanding kapitalisme yang direpresentasikan oleh TPL. International Cooperative Alliance mendefinisikan koperasi sebagai “usaha-usaha yang berpusat pada rakyat, dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh dan untuk anggota untuk merealisasikan kebutuhan dan aspirasi budaya, sosial, dan ekonomi bersama”. Dengan kata lain, filosofi kooperativisme mempercayai bahwa kesejahteraan sosial sejati hanya dapat diraih jika rakyat sendiri mengorganisir diri secara kolektif dan demokratis, tidak bergantung pada bantuan luar, termasuk filantropi dan dana sosial perusahaan.
Menurut data World Cooperative Monitor 2023, ada 300 koperasi di dunia yang berkembang dengan nilai aset bahkan melebihi korporasi besar di negara masing-masing. Salah satu contoh koperasi terbesar yang sukses di dunia adalah Mondragon Cooperative Corporation (MCC) atau Koperasi Mondragon. Koperasi Mondragon adalah sebuah grup perusahaan besar di wilayah Basque, kota Mondragon, Spanyol yang beroperasi dalam empat sektor utama, yakni finansial, industri, retail, dan ilmu pengetahuan (Romeo, 2022). Koperasi Mondragon didirikan pada tahun 1956 oleh seorang pastor Katolik, José María Arizmendiarrieta, yang menyebarkan ajaran keadilan sosial pada empat buruh pabrik untuk mengembangkan usaha alternatif yang lebih demokratis karena proposal mereka untuk pembagian saham para pekerja pada perusahaan lama tempat mereka bekerja ditolak (Whyte & Whyte, 1991). Pada tahun 2022, MCC telah membawahi 81 perusahaan kooperasi dengan lebih dari 70 ribu pekerja, 12 pusat riset dan pengembangan, 104 cabang luar negeri, dan mencapai total penjualan 10.607 juta euro atau sekitar Rp 184 triliun pada tahun 2022 (Mondragon, 2022). Total aset Koperasi Mondragon bahkan mampu menandingi aset-aset korporasi di Spanyol yang menggunakan model manajemen kapitalisme.
Berbeda dengan korporasi umumnya yang pemilik saham mayoritas menentukan semua keputusan bisnis termasuk menunjuk direksi perusahaan melalui RUPS tanpa melibatkan pekerja, model bisnis Koperasi Mondragon menerapkan prinsip-prinsip kooperasi dimana satu anggota memiliki hak memilih dan bersuara dalam Rapat Umum untuk penentuan keputusan-keputusan strategis. Koperasi Mondragon juga mengatur rasio gaji antara karyawan level terendah dengan gaji tertinggi sebesar 1:6 kali, yang sangat kontras dengan rasio gaji di berbagai korporasi yang dapat mencapai 1:2000, termasuk TPL. Penerapan model manajemen demikian telah membuktikan bahwa para pekerja-anggota Koperasi Mondragon memiliki kontrol masa depan ekonomi mereka, tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya (Arregi et al., 2022; Rodríguez-Oramas et al., 2022). Salah satu kunci keberhasilan Koperasi Mondragon dalam mengembangkan dirinya adalah memiliki pendidikan dan pelatihan kader ideologis koperasi yang intensif dan mengembangkan pusat riset koperasi sehingga pengambilan keputusan mereka berbasis hasil riset.

Koperasi Mondragon dapat menjadi inspirasi pengembangan KPAM Wilayah Tano Batak di Indonesia. Sejauh pengamatan saya ketika berkeliling, banyak potensi produk di Komunitas yang produk turunannya dapat dikembangkan seperti haminjon, nenas, kopi, dan jagung juga alat musik tradisional, tenun ulos, dan lain sebagainya. Koperasi ini perlu dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip kearifan Adat yang mengajarkan hubungan hormat dengan Tuhan, alam, dan sesama. Ini adalah pembuktian pada pemerintah bahwa tanpa TPL, komunitas-komunitas Masyarakat Adat dapat percaya diri mengorganisir Koperasi berbasis keberagaman potensi lokal yang mensejahterakan semuanya, bukan segelintir orang. Jika pemerintah enggan menutup TPL dengan alasan investasi, penciptaan lapangan kerja dan bayar pajak, maka Koperasi ini juga akan membuktikan membuka lapangan kerja lebih masif, tidak merusak alam, dan membayar pajak dengan taat pada negara. Tentu saja tidak akan melakukan manipulasi ekspor dan pajak seperti yang dilakukan oleh TPL.
Berdasarkan diskusi saya dengan kawan-kawan di AMAN Tano Batak, pekerjaan rumah untuk mengembangkannya adalah membutuhkan kader-kader yang paham ideologi Koperasi sekaligus cara manajemennya. Saya mengusulkan beberapa tahap pengembangan: 1) Melakukan studi etnografi tentang potensi dan perilaku ekonomi Komunitas Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi orientasi berkoperasi, dan mengidentifikasi dan mendiskusikan produk unggulan komunitas; 2) Melakukan studi khusus tentang kearifan dan sistem ekonomi Batak Toba pra-kolonial untuk menggali kearifan luhur yang dapat direvitalisasi di KPAM; 2) Mengadakan Pendidikan Kader Ideologis Koperasi dengan melibatkan staf, pemuda adat, dan anggota-anggota Komunitas Masyarakat Adat yang tertarik. Materi-materinya dapat meliputi mode produksi perusahaan-perusahaan kapitalis dan kerusakan-kerusakannya, analisis rentenir dan tengkulak di desa, filosofi dan manajemen koperasi sebagai lawan tanding kapitalisme, manajemen keuangan, dll; 3) Setiap peserta pendidikan tersebut ditugaskan mengorganisir kelompok usaha di Komunitas untuk menghidupkan filosofi marsirimpa (gotong royong) di bidang ekonomi sebagai landasan filosofis koperasi yang berlandaskan kepercayaan diri atas kekuatan kolektif; 4) Setelah produk unggulan disepakati berdasarkan Musyawarah Adat di tiap komunitas, setiap produsen berkumpul untuk menyepakati besaran saham kepemilikan dalam KPAM dan melakukan musyawarah pemilihan pengurus Koperasi; 5) Pengurus KPAM terpilih melakukan pengembangan manajemen dan organisasi yang fokus pada penelitian dan pengembangan produk serta valuasi ekonomi komunitas, penelitian dan pengembangan pasar, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem penggajian yang tidak timpang, dan pemasaran. Tahapan pengembangan ini tentu saja dapat disesuaikan sesuai arahan Pengurus Besar AMAN yang memiliki pengalaman praksis dalam mendirikan KPAM.
Sebagai tambahan, saya tidak mengatakan bahwa model bisnis koperasi terbebas dari kecenderungan adanya oligarkisasi elit yang ingin memonopoli kuasa manajerial di dalamnya sebagaimana juga yang sedang dialami Mondragon (Unterrainer et al., 2022). Namun, Koperasi Mondragon juga memiliki forum Refleksi Kritis rutin tentang demokratisasi ekonomi dimana para pekerja yang sudah mendapatkan pendidikan ideologis Koperasi terbuka mengkritik para pengurus yang elitis tanpa takut akan dipecat karena merupakan haknya untuk bersuara (Etxagibel et al., 2012). Ini juga nantinya dapat diterapkan di KPAM Tano Batak.
Penutup
Belakangan, ada diskusi yang berkembang di kalangan akademisi, aktivis, dan pemerintah tentang usaha mendamaikan bisnis dan hak asasi manusia. Pemerintah bahkan telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Namun, terkait dengan hal ini, saya ingin mengulangi kalimat saya di bagian sebelumnya dari tulisan ini: Tidak akan ada perdamaian antara bisnis dengan hak asasi manusia dan hak asasi alam jika ideologi bisnisnya kapitalistik. Sistem ekonomi yang mengakumulasi modal di tangan segelintir orang tidak akan berhenti mengajarkan perusahaan untuk terus ekspansi bisnis dan merampas tanah rakyat demi memuaskan keserakahannya. Sebagai solusi, kita perlu menerapkan prinsip ideologi Koperasi sebagai amanat konstitusi yang juga diajarkan salah satu proklamator kita, Mohammad Hatta, untuk memastikan demokrasi ekonomi betul-betul terwujud nyata di Indonesia.
Logika penjajahan memang adalah mematikan imajinasi rakyat yang dijajah tentang hidup yang lebih baik menurut cara/pengetahuan/kearifan mereka sendiri. Perspektif dekolonisasi mengajarkan bahwa pemerintah dan TPL tidak perlu mendikte Masyarakat Adat tentang bagaimana cara untuk sejahtera. Dengan kata lain, mengikuti istilah zaman sekarang, pemerintah dan TPL tidak perlu merasa ‘si paling lapangan kerja’ atau ‘si paling investasi’ seolah-olah Masyarakat Adat menganggur dan tidak memiliki kekayaan alam untuk dikelola secara berdaulat. Pemerintah sahkan saja RUU Masyarakat Adat, laksanakan reforma agraria sejati, dan adili kejahatan korporasi TPL dan Sukanto Tanoto! Jangan tahunya menghianati rakyat saja dan berselingkuh dengan para oligarki!
Penulis adalah Dosen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta dan Mahasiswa S3 School of Business, University of Queensland, Australia.
Daftar Pustaka
Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. Sustainability (Switzerland), 14(6), 1–16. https://doi.org/10.3390/su14063415
Adler, P. S., Forbes, L. C., & Willmott, H. (2007). Critical management studies. The Academy of Management Annals, 1(1), 119–179. https://doi.org/10.4324/9781315524771-10
Azhari, I., & Sinaga, R. (2022). Tuan M.H. Manullang Pahlawan Indonesia dari Tanah Batak (1887-1979). Literasi Nusantara Abadi.
Banerjee, S. B. (2000). Whose land is it anyway? National interest, indigenous stakeholders, and colonial discourses: The case of the Jabiluka uranium mine. Organization and Environment, 13(1), 3–38. https://doi.org/10.1177/1086026600131001
Banerjee, S. B. (2003). The Practice of Stakeholder Colonialism: National Interest and Colonial Discources in the Management of Indigenous Stakeholders. In A. Prasad (Ed.), Postcolonial Theory and Organizational Analysis. Palgrave Macmillan. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results
Banerjee, S. B. (2008). Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly. Critical Sociology, 34(1), 51–79. https://doi.org/10.1177/0896920507084623
Banerjee, S. B. (2022a). Decolonizing Deliberative Democracy: Perspectives from Below. Journal of Business Ethics, 181(2), 283–299. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04971-5
Banerjee, S. B. (2022b). Decolonizing Management Theory: A Critical Perspective. Journal of Management Studies, 59(4), 1074–1087. https://doi.org/10.1111/joms.12756
Banerjee, S. B., & Arjaliès, D.-L. (2021). Celebrating the End of Enlightenment: Organization Theory in the Age of the Anthropocene and Gaia (and why neither is the solution to our ecological crisis). Organization Theory, 2(4), 1–24. https://doi.org/10.1177/26317877211036714
Banerjee, S. B., & Berrier-Lucas, C. (2022). Foreword decolonizing the business schools: A journey on paths less travelled. Responsible Organization Review, 2(October), 36–41.
Choudhury, C., & Aga, A. (2020). Manufacturing Consent: Mining, Bureaucratic Sabotage and the Forest Rights Act in India. Capitalism, Nature, Socialism, 31(2), 70–90. https://doi.org/10.1080/10455752.2019.1594326
Etxagibel, J. A., Cheney, G., & Udaondo, A. (2012). Worker’s Participation in a Globalized Market: Reflections on and from Mondragon. In M. Atzeni (Ed.), Alternative Work Organizations (pp. 76–102). Palgrave Macmillan.
FAO. (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. Global Forest Resources Assessment 2020. https://doi.org/10.4060/ca9825en
Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in Stakeholder Theory. Business and Society, 59(2), 213–231. https://doi.org/10.1177/0007650318773750
Henry, E., Newth, J., & Spiller, C. (2018). Emancipatory Indigenous social innovation: Shifting power through culture and technology. Journal of Management & Organization, 6(2017), 786–802. https://doi.org/10.1017/jmo.2017.64
Isbell, F., Balvanera, P., Mori, A. S., He, J. S., Bullock, J. M., Regmi, G. R., Seabloom, E. W., Ferrier, S., Sala, O. E., Guerrero-Ramírez, N. R., Tavella, J., Larkin, D. J., Schmid, B., Outhwaite, C. L., Pramual, P., Borer, E. T., Loreau, M., Omotoriogun, T. C., Obura, D. O., … Palmer, M. S. (2023). Expert perspectives on global biodiversity loss and its drivers and impacts on people. Frontiers in Ecology and the Environment, 21(2), 94–103. https://doi.org/10.1002/fee.2536
King, D., & Learmonth, M. (2015). Can critical management studies ever be ‘practical’? A case study in engaged scholarship. Human Relations, 68(3), 353–375. https://doi.org/10.1177/0018726714528254
Lenton, T. M., Xu, C., Abrams, J. F., Ghadiali, A., Loriani, S., Sakschewski, B., Zimm, C., Ebi, K. L., Dunn, R. R., Svenning, J. C., & Scheffer, M. (2023). Quantifying the human cost of global warming. Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-023-01132-6
Manalu, H., Simanjuntak, R., & Nainggolan, W. (2021). Ritual Adat di Tengah Perampasan Ruang Hidup (Aliansi Masyarakat Adat Tano Batak). Penerbit Pelana: Medan.
Mondragon. (2022). 2022 Annual Report. In Mondragon Cooperative Corporation. https://www.mondragon-corporation.com/
Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. Journal of Peasant Studies, 44(3), 594–630. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036
Moore, J. W. (2018). The Capitalocene Part II: accumulation by appropriation and the centrality of unpaid work/energy. Journal of Peasant Studies, 45(2), 237–279. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1272587
Nicholson, A., Spiller, C., & Pio, E. (2019). Ambicultural Governance: Harmonizing Indigenous and Western Approaches. Journal of Management Inquiry, 28(1), 31–47. https://doi.org/10.1177/1056492617707052
Parker, M. (2018). Shut Down The Business School! What’s Wrong with Management Education. Pluto Press.
Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. Academy of Management Annals, 4(1), 403–445. https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581
Romeo, N. (2022, August 27). How Mondragon Became the World’s Largest Co-Op. The New Yorker. https://www.newyorker.com/business/currency/how-mondragon-became-the-worlds-largest-co-op
Savitri, L. A., Larastiti, C., & Luthfi, A. N. (2019). AMAN Dua Dekade: Memperjuangkan Hak, Memperjuangkan Kemajemukan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Scheidel, A., Fernández-Llamazares, Á., Bara, A. H., Bene, D. Del, David-Chavez, D. M., Fanari, E., Garba, I., Hanaček, K., Liu, J., Martínez-Alier, J., Navas, G., Reyes-García, V., Roy, B., Temper, L., Aye Thiri, M., Tran, D., Walter, M., & Whyte, K. P. (2023). Global impacts of extractive and industrial development projects on Indigenous Peoples’ lifeways, lands, and rights. Science Advances, 9(23), 33–35. https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9557
Shiva, V. (2015). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. North Atlantic Books.
Shiva, V. (2020). Reclaming the Commons: Biodiversity, Indigenous Knowledge, and the Rights of Mother Earth. Synergetic Press.
Smith, L. T. (2021). Decolonizing Methodologies (Third Edit). Bloomsbury Publishing.
Spiller, C., Pio, E., Erakovic, L., & Henare, M. (2011). Wise Up: Creating Organizational Wisdom Through an Ethic of Kaitiakitanga. Journal of Business Ethics, 104(2), 223–235. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0905-y
Suroto. (2023). Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme. Mata Kata Inspirasi.
Unterrainer, C., Weber, W. G., Höge, T., & Hornung, S. (2022). Organizational and psychological features of successful democratic enterprises: A systematic review of qualitative research. Frontiers in Psychology, 13, 1–33. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.947559
Warburton, E. (2024). Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia. Critical Asian Studies, 1–23. https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069
Whyte, W. F., & Whyte, K. K. (1991). Making Mondragon: The Growth and Dynamics of The Worker Cooperative Complex. ILR Cornell University Press.
World Metereological Organization. (2023). Global Annual to Decadal Climate Update. In WMO. https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=22272
WWF. (2022). Living Planet Report 2022 – Building A Nature-Positive Society. https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2021/articles/a-warning-sign-where-biodiversity-loss-is-happening-around-the-world